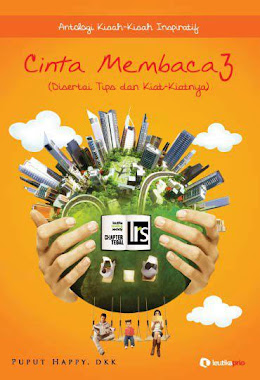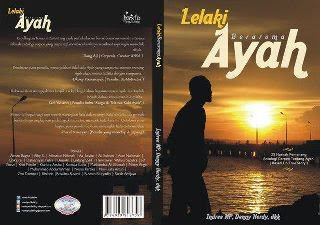Udara begitu dingin. Mengerogoti tubuh menyisakan
ngilu yang menusuk tulang. Gemericik gerimis diluar melambai menyurut birahi.
Jalanan sepanjang Messacuset Country merangkakkan hujan yang semakin menjadi. Tak
ada salju setiap bulan terakhir. Udara bulan Desember yang sudah 3 tahun aku
lalui disini seakan mudah aku hafal. Entah mengapa setiap Desember datang,
nyaliku seakan padam. Semua kekuatan yang menjadikanku bertahan disini, sekejap
luluh. Aku mencoba menerawang kejadian itu. Sudah lama memang, namun tak mudah
untuk dilupakan.
*******
Aku sendirian.
Menatap hamparan sabana yang belum pernah aku temui
sebelumnya. Tak ada pandangan istimewa di depanku. Semua seakan diam. Entahlah
hal apa yang membuatku terus berlama-lama di tempat ini. Satu menit tak ada
sesuatu yang menarik. Menit kedua juga demikian. Ketiga dan keempat bahkan satu
jam lamanya aku terpaku. Hanya memandangi ilalang yang diterpa angin.
Aku mulai bosan.
Aku mengikuti langkah kaki yang membawaku menjauhi
tempat itu. Suara gesekan sepatu kets yang kupakai menjadi nada tersendiri.
Terdengar suara lain yang aku yakin bukan aku yang membuatnya. Suara itu terus
mengikuti ritme langkahku. Kulirik sekelilingku. Kosong. Aku berhenti karena
merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Tak ada siapapun di tempat luas ini. Hanya
ilalang yang tetap bergoyang serta angin yang berkolaborasi dengan kesibukannya
hujan. Tak lama seakan bulu kudukku merinding. “Ah, persetan!”. Aku terus
berjalan menapaki arah yang sepertinya tanpa batas. Tarian ilalang kini mulai
tak berirama. Goyangannya pun liar menciptakan penampilan yang menakutkan.
Terlintas di benakku sosok Suzanna hantu yang melegenda. Film klasik yang belum
lama ini aku tonton di laptopku. Ia bersembunyi di antara ilalang yang tengah
bermain liar. Terlihat kembang sundel yang sering menghiasi gulungan rambutnya.
Ia menatapku tajam. Aku bergidik ngeri. Aku menghindari tatapan yang membuat
keringatku mengucur deras. Aku berlari dengan tertatih-tatih. Seakan Suzanna
mengejarku. Menerkamku dan membuatku limbung dalam dekapannya. Ia tak berhenti
disitu, aroma kembang sundel menyeruakkan aura mistis. Tawanya yang khas
memecah angin yang bersiar-siur. Tawanya memaksa masuk paling dalam dari rasa
ketakutan manusia.
Aku terjebak di tengah angin dan hujan yang mulai mengganas. Di tempat asing dengan suasana mencekam. Aku mempercepat langkah, menepis segala praduga dan pikiran yang meluap-luap bagai lahar di kepala. Ini adalah ketakutan semu. Aku berlari menghindari tempat terkutuk ini. berusaha menghindari tangan-tangan yang asing menyentuhku. Dari ilalang yang menjuntai tinggi itu, Suzanna menerkamku tiba-tiba. Menyeretku ke tengah rerimbun rerumputan. Dengan ganas ia membuka pakaianku. Secara paksa. Aku mencoba melawan, tapi gagal. Ia menelanjangiku hingga raut senyum tergambar di wajahnya. Keringatku mengucur. Tak hanya sampai disitu, tangannya yang terubah kokoh kini mencengkeram leherku. Ia jilati leherku terus ke atas hingga hampir menyentuh bibirku. Ia terhenti. Mungkin keringatku tak sedap baginya. Aku salah, cengkeramannya semakin kuat. Dengan kuku yang menghitam runcing ia tusuk bibirku. “Arggghhh,” aku merintih pilu. Aku mencoba meronta tapi adegannya kembali terulang pada mataku. Ia cungkil dan ia keluarkan perlahan. Ia bisa melakukannya. Mataku ia mainkan seakan itu sebuah gundu. Darah yang memoles pipiku keluar segar. Amis dan merah kental.
Aku meraung.
Arrrrrrrgggghhhh!!!!!!!
Riaaaaannnnnnnn!!!!!
Sahabatku Mr.Linco mengguncangkan tubuhku. Di goyangkan tubuh ini hingga aku tersadar. Di berikannya minum yang biasa aku letakkan diatas meja kerjaku. Ia berkata aku menceracau sambil berteriak-teriak. Mimpi yang sama seperti mimpi-mimpi yang hadir pada malam-malam Desember sebelumnya. Mimpi yang selalu meneror kehidupanku. Mimpi yang membuat hidupku kacau. Dan mimpi yang membuatku mengingatkan pada seseorang. Nafasku masih memburu. Butiran jagung cair keluar dari pori-pori kulitku.Di luar angin berhembus kencang. Hujan di luar rupanya sudah reda. Aku berdiri dari kursi kerja yang telah menidurkanku. Kuberjalan menambahkan kayu bakar pada perapian. Kutatap jendela kaca tepat di atasnya. Sengaja aku berlama mencerna dan menyimpulkannya dengan rona malam. Sesuatu yang aku sendiri sudah memprediksi.
Kubenamkan kembali wajah dalam bantal. Mencari
kembali serpihan ketenangan dalam tidur menjelang dua dini hari.
*******
“Lebih baik kau pulang sejenak, ambil cuti saja. Toh selama ini cutimu belum kau gunakan sama sekali,” Hera tersenyum menatap kegundahanku. Hera adalah rekan kerja sebangsaku. Garis Jawa yang berkombinasi dengan Thailand tak menampik mempunyai tubuh yang proporsional. Awal aku kenal dengan dia ketika masa-masa kuliahku dulu di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Tak ada hubungan spesial antara aku dengannya, karebna perbedaan agama menjadi alasan kami berkenalan lebih jauh. Ia menghormati agama nasraninya sedangkan aku menjunjung tinggi islamku. Namun begitu, rasa saling menghormati selalu tercipta diantara persahabatan kami.
“Aku takut dia masih tak memaafkanku Ra,” kali ini
aku mulai mengkapkan rasa bersalahku padanya.
“Sudahlah Jef, seiring waktu berlalu pasti ada penyesalan atas masalah kalian. Aku yakin, tak hanya kamu yang mengalami ini. Dia juga pasti menyadari kesalahanmu,” aku mengangguk. Di berikannya tissue itu dari dompet make up-nya.
*******
“Kau penghianat Jef, tega-teganya kau hancurkan duniaku. Apa salahku hingga kau berbuat begitu, heh..!!!!,” Rian menahan amarahnya. Di genggamnya tangan itu. Ia sudah siap untuk meninjukan kepalan tangannya.
“Maaf Yan, aku tak bermasksud melakukan itu poadamu. Demi tuhan Yan, aku menyesal,” Rian hanya diam. Tersirat kepedihan pada matanya. Tangannya mulai melonggar.
“Sudah dari awal kubilang jangan terlalu percaya wanita itu. Kau sudah termakan perangkapnya. Bukan hanya itu, kau tahu apa yang terjadi dengan aku dan juga keluargaku?,” Aku terus menunduk menahan malu menghindari tatapan matanya.
“Kau benar lebih mementingkan wanita pujaanmu itu. Tak sadar kau tak mementingkan hatiku Jef. Aku dengan Rani bertahun-tahun merintis usaha ini. Dan akhirnya usaha itu semakin berkembang. Lalu, kau datang. Aku sudah menganggapmu sebagai saudara sendiri Jef. Akupun pernah berkata jangan terlalu percaya pada wanita yang baru kau kenal. Dan ini hasil dari kelengahanmu. Tak lama lagi kita akan ditendang dari rumah ini. Kau bodoh Jef! Bodoh!!!!!! Pergi kau!!!!!!!,” Rian begitu emosi. Terlihat Mbak Rani menenangkan suaminya. Aku melangkahkan kaki keluar rumah yang telah memberiku arti selama ini.
*******
Aroma Zamrud Khatulistiwa meyeruak di hidungku.
Masih tak percaya aku telah kembali ke tanah perantauan ini. Rasa ini persis
seperti pertama kali aku meninggalkan kota ini. Tak habis waktu aku mengingat
pertengkaran dengan Rian sahabatku. Aku semakin gundah tatkala taxi yang aku sewa
memasuki pekarangan rumah Rian. Terlihat sepi rumah yang masih sama 3 tahun
yang lalu. Tak ada orang yang berseliweran yang dapat menandakan rumah itu
berpenghuni.
“Maaf mas, ini rumahnya Mas Rian kan?,” tanyaku pada seorang yang berada pada rumah sebelahnya.
“Tidak mas, Pak Rian dan istrinya pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Kidul,” ternyata benar. Rumah itu bukan milik Rian dan Mbak Rani lagi. Penyesalanku semakin bertambah besar. Orang itu membalas ucapan terima kasihku. Pernah 5 tahun lalu aku diajak Rian kerumah orang tuanya. Saat itu hubunganku memang lagi baik-baiknya. Aku lupa-lupa iongat alamat rumah ibu Rian. Jalanan yang masih beralaskan tanah membuat kesan tersendiri. Tak seperti dulu, kanan kiri jalanan sudah di bangun rumah-rumah. Aku hampir lupa gang menuju rumah ibu Rian. Semua berubah selama beberapa tahun belakangan. Hingga aku harus turun jalan kaki karena taxi tidak bisa memasuki gang yang akan mengantarkanku bertemu Rian. Sudah dekat. Tak butuh hitungan kilometer lagi. Cukup beberapa langkah rumah bercat biru tua terpampang jelas. Bangunannya masih seperti yang dulu. Bahkan kolam ikan buatanku dengan Rian masih terjaga.
Terlihat sosok itu. Lelaki berambut ikal tengah
menyuapi seorang bocah. Apakah itu anaknya?
Apakah ia ingat dengan aku? Apakah perlakuannya akan sama seperti waktu
itu?. Pikiranku mulai ragu untuk melangkahkan selangkah kakiku. Hinga dia
menyadari kehadiranku.
“Kamu….,” aku mengangguk pelan.
“Rian, maafkan salahku selama ini. Aku mohon Yan, aku terbebani atas semua kejadian kala itu,” Rian masih memasang wajah melongo. Seakan aku adalah hantu baginya.
“Jefri, benarkah itu kau Jef?,” aku mengangguk. Rian mengangkat bahuku yang tengah merengkuh kakinya. Ia dekap aku layaknya aku adalah istrinya.
“Yan, maafkan aku…..,” bisikku pelan di telinganya.
“Sudahlah Jef, aku tak bisa berlama-lama marah denganmu. Kau sahabatku. Kemana saja kau selama ini?.”
“Maaf Yan, aku tak ingin buat keluargamu susah lagi. Aku pergi dan aku mencoba mencari pekerjaan. Hingga Hera mengajakku bekerja di Boston Yan, kau masih ingatkah dengan Hera sahabat kita?,” Rian mencoba berpikir. Membuka kembali memori yang selama ini tertimbun.
“Hera yang sering bantu kamu mencari bahan skripsi dulu Yan!,” aku mencoba membantu mengingatkannya.
“Oh iya, aku baru ingat. Bagaimana kabarnya?”
“Baik yan,” jawabku singkat.
“Berkat dia aku berani menemuimu. Aku sudah kuat bila perlakuanmu masih seperti saat itu,” tambahku.
“Memang Jef, kemampuan bahasamu dari awal kuliah sudah bagus, pantas kau diterima di sana. Sudahlah
aku sudah melupakan itu,” Tiba-tiba suara ibu-ibu mengagetkan perbincangan kami.
“Jefri……!!! Kamu kan itu?,” Mbak Rani masih ingat denganku. Aku menjabat tangannya. Mbak Rani ikut mengobrol juga. Tak disangka Mbak Rani semakin keibuan.
“Anakmu Yan?,” tanyaku ketika gadis kecil naik ke pangkuannya.
“Iya,” jawab Rian yang kemudian dilanjut dengan ucapan Mbak Rani.
Lama perbincangan kami. Hingga membahas
masing-masing pekerjaan kami sekarang hingga masalah 3 tahun yang lalu.
Ternyata keluarga Rian sudah memaafkanku sudah lama. Bahkan meraka mencariku,
karena khawatir atas riwayatku yang tak mempunyai keluarga di sini. Rian dan
juga Mbak Rani ternyata bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Sungguh berbeda
saat dulu mereka mengelola TOSERBA keluarganya.
“Oh ini Yan, hampir aku lupa. Aku ada oleh-oleh sedikit,” aku serahkan bingkisan itu pada mereka.
“Boleh dibuka Yan?,” aku mengangguk kecil. Aku bersiap melihat dunia mereka yang tak lama akan berubah.
“Surat tanah?!?!,” Rian nampak kebingungan begitu pula mbak Rani lalu melihatku.
“Baca dulu Yan?,” jawabku.
“Maksudnya ini apa, aku tak mengerti Jef!,” suara Rian kini mulai kalut. Di lemparkannya surat itu ke pangkuanku. Entah apa yang ada di pikirannya.
“Untuk keluarga mu Yan, itu surat beli tanah TOSERBAMU dulu,” terlihat Mbak Rani mulai mengerluakan air mata.
“Bagaimana kamu mendapatkan ini Jef, kamu menemui wanita ular itu?”
“Bukan Yan, wanita ular itu telah lama menjual TOSERBA kalian, seminggu setelah aku memberikan surat tanah milikmu dulu. Maafkan aku Yan, aku buta karena cinta. Aku tak melihat ada kalian yang sudah menganggap aku keluarga. Ini aku beli kembali untuk aku kembalikan pada kalian. Maaf bila aku selama ini meyusahkan hidup kalian,” linangan air mata Mbak Rani membuat aku dan Rian juga terbawa suasana.
“Terimalah Yan,” aku memeluk Rian. Hal ini yang lama aku rindukan dari hangat sahabat yang menyayangiku lebih dari sekedar keluarga.
Persahabatan bukanlah tentang apa yang kita punya
tetapi tentang apa yang kita berikan, yaitu kasih sayang dan maaf yang setulus
hati…..
(J. Setyawan)